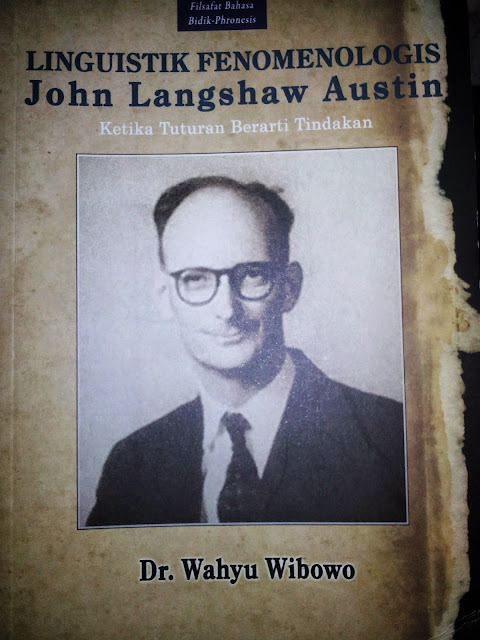Wednesday, October 15, 2014
Pendahuluan; Gerak Substansi dan Gerak Cinta
Sekilas Mengenai Perempuan dalam Quran
Thursday, October 9, 2014
ESKATOLOGI (MA’AD)
- Tuhan
itu MahaBenar dan tidak melakukan pekerjaan yang batil dan sia-sia. Proposisi
‘alam tak memiliki tujuan’ adalah proposisi yang salah. Karena itu alam
ini memiliki tujuan yaitu mendapatkan ketenangan dan kedamaian di alam
sana. Alam tersebut disebut dengan alam akhirat.
- Tuhan
MahaBijaksana. Dan Tuhan MahaBijaksana tidak berbuat sesuatu yang bertentangan
dengan hikmah dan keadilan. Demikian halnya bahwa Tuhan itu MahaAdil
sehingga Tuhan memberikan ganjaran pada siapa yang berhak. Karena di dunia
yang kita saksikan ini, tidak memberikan jaminan sepenuhnya untuk membalas
kebaikan dan kesalahan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mesti ada
satu masa yang dapat membalas amal-amal manusia. Dan masa itu adalah hari
kiamat.
- Keniscayaan
dari rahmat Ilahi adalah mengantarkan manusia pada kesempurnaannya. Oleh
karena itu mesti ada kiamat sehingga manusia dapat menyaksikan amal perbuatannya
sendiri dan sekaligus menyampaikannya pada kesempurnaan.
- Dalam
surah Yasin ; 78 dijelaskan, Tuhan yang pada saat pertama kali menciptakan
manusia, mampu untuk menciptakan kembali manusia tersebut seperti
sediakala.
- Meskipun
karekteristik badan senantiasa berubah, namun jiwa itu tetap dan menjadi
penentu identitas personal badan. Oleh karena itu, keseluruhan badan dan jiwa
di dunia akan dibangkitkan kembali di alam akhirat.
- Wujud
adalah kebaikan dan pengetahuan terhadapnya adalah bentuk kebaikan
lainnya. Semakin sempurna wujud, semakin sempurna pula kebaikan. Oleh karena
itu, eksistensi fakultas akal lebih unggul dan kebahagiaan baginya pun
lebih besar. Kenikmatan yang dihasilkan dari persepsi-persepsi tersebut
tak dapat dibayangkan, karena akal dari sisi persepsi lebih kuat dari
persepsi indrawi. Namun kebaikan-kebaikan ini tak diperoleh selama jiwa
masih melekat dengan badan duniawinya, ketika terpisah, barulah teraktual.
- Jiwa
mampu sampai pada maqam tertentu dimana kebergantungannya pada badan
semakin sedikit dan jiwanya lebih besar tertuju pada alam lain. Kematian
akan membuat badannya terpisah dengan jiwanya. Keterpisahan ini bukan
karena ketidakmampuan jiwa dalam menjaga badannya, namun dikarenakan
secara fitrawi jiwanya lebih tertuju ke alam sana.
Tuesday, October 7, 2014
Resensi Buku; Ketika Tuturan Berarti Tindakan
JUDUL BUKU : LINGUISTIK FENOMENOLOGI JOHN LANGSHAW AUSTIN “KETIKA TUTURAN BERARTI TINDAKAN”
PENULIS : Dr. WAHYU WIBOBO
PENERBIT : BIDIK-PHRONESIS PUBLISHING, JAKARTA
TAHUN TERBIT : CETAKAN 1, 2011
TEBAL HALAMAN : xiv+138 hal; 14 cm x 21 cm
Buku ini oleh penulis, disuguhkan untuk menjelaskan pemikiran utama John Langshaw Austin yaitu berkenaan dengan Filsafat Bahasa Biasa. Penulis buku ini membagi pokok pikirannya menjadi empat bagian. Bagian pertama meliputi sejarah singkat dan istilah Filsafat Bahasa dan perbedaannya dengan istilah lainnya seperti Linguistik Struktural dan Filsafat Analitik. Bagian kedua menjelaskan pandangan spesifik Austin tentang Linguistic Phenomenology. Bagian kedua dapat dikatakan gagasan inti dari buku ini karena dasar pemikiran Austin lebih banyak dituangkan pada bagian kedua. Sedangkan bagian ketiga dan bagian keempat memaparkan bagian aplikatif atau aksiologis Filsafat Bahasa Biasa.
Persoalan dan kajian-kajian filsafat pada awal abad 20, lebih banyak pada analisa bahasa beserta maknanya, khususnya di Amerika dan Eropa seperti Inggris. Pada pendahuluan buku ini yang oleh penulis menyebut pendahuluan ini dengan prawacana, menegaskan Ludwig Wittgenstein sebagai pencetus aliran Filsafat Bahasa Biasa dan kemudian dilanjutkan Austin. Wittgenstein yang membangun dasar-dasar baru teori bahasa, sedangkan Austin yang mengaplikasikannya. Penulis juga menjelaskan bahwa Filsafat Kontemporer mencatat aliran filsafat Bahasa Biasa sebagai aliran pemikiran yang paling kritis dan paling berpengaruh, terutama karena (a) upayanya dalam mengoreksi pemikiran strukturalisme bahasa, dan (b) pengaruhnya dalam kelahiran sejumlah pemikiran kritis lainnya yang datang belakangan, seperti teori kritis Habermas, Hermeneutika Kritis Gadamer, Poststrukturalisme Derrida, dan Postmodernisme Lyotard.
Penelitian dan analisa kritis terhadap bahasa menjadi penting, paling minimal dikarenakan oleh dua hal: pertama karena bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga dikarenakan aspek inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kedua, kebanyakan kesalahan-kesalahan dalam pikiran manusia dikarenakan penggunaan yang tidak benar dan tidak benar dalam menggunakan bahasa. Tak heran jika sebagian dari Filsuf Bahasa menklaim kemunculan Filsafat Bahasa adalah tanda kematian bagi aliran-aliran filsafat yang ada sebelumnya. Meskipun saat ini klaim mereka tidak memiliki dampak yang signifikan namun dapat terlihat sumbangsih yang telah diberikan atas analisa filosofis terhadap bahasa.
Wittgenstein berpandangan bahwa kesalahan kaum filsuf sebelumnya dikarenakan mereka melampaui batas bahasa padahal bahasa memiliki batasan tersendiri. Bahkan kata Wittgenstein, tugas filsafat bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan filsafat, akan tetapi tugas utama filsafat ialah menghancurkannya. Menurut Wittgenstein (First Wittgenstein), manusia mampu memaparkan realitas melalui perantara bahasa. Menurutnya struktur bahasa dan realitas itu satu. Analisa komprehensif terhadap struktur bahasa mampu menjelaskan struktur realitas. Bahasa adalah gambaran realitas karena terdiri dari proposisi-proposisi yang menjelaskan realitas.
Dr. Wahyu Wibowo pada bagian pertama juga menjelaskan bahwa Filsafat Bahasa bahkan dianggap memiliki metode yang kritis dan netral karena mampu membersihkan bahasa para filsuf sebelumnya dari pemikiran yang melingkar-lingkar tidak jelas dan tidak terlibat dengan realitas. Selain hal ini, metode yang digunakan filsafat bahasa juga dianggap sebagai metode yang khas dalam ilmu filsafat, karena selain digunakan untuk mencari hakikat bahasa juga sekaligus dapat dijadikan teori untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan bahasa.
Sebelum melangkah lebih jauh, buku ini menjelaskan asal muasal aliran Filsafat Bahasa Biasa bahwa, akar Filsafat Bahasa ini berasal dari Atomisme Logis dan Positivisme Logis. Sebagaimana dipahami, kaidah penting dan mendasar dalam Positivisme Logis adalah prinsip verification. Melalui kaidah ini kaum Positivisme meyakini mampu memilah secara nyata antara proposisi yang memiliki makna dengan proposisi yang tak memiliki makna. Proposisi yang memiliki makna ialah proposisi analitik dan proposisi sintetik. Proposisi analitik ialah proposisi yang berkaitan dengan logika dan matematika, sedangkan proposisi eksprementasi adalah proposisi sintetik. Namun proposisi yang tidak termasuk ke dalam proposisi analitik dan sintetik adalah proposisi yang tidak memiliki makna.
Istilah Filsafat Bahasa mesti dibedakan dari Linguistik Struktural. Linguistik Struktural menjelaskan bahwa bahasa tunduk di bawah hukum linguistik, sedangkan Filsafat Bahasa justru menjelaskan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Filsafat Bahasa, bahasa hanya dapat dipahami dalam format bentuk-bentuk kehidupan yang merupakan konteks bagi pemakaian bahasa itu sendiri. Kehidupan yang kompleks ini berimplikasi pada penggunaan bahasa untuk bermacam-macam tujuan.
Isitilah selanjutnya yang mesti dibedakan ialah antara Filsafat Bahasa dan Filsafat Analitik, apalagi kedua istilah ini sering diidentikkan. Penulis buku ini menjelaskan, dari sudut hakikatnya, kedua istilah ini memang identik karena para filsufnya sama-sama menjadikan bahasa sebagai objek material mereka. Penulis menjelaskan lebih jauh bahwa perbedaan antara Filsafat Bahasa dengan Filsafat Analitik terletak pada fungsi dan cakupan diantara keduanya. Khususnya dalam pandangan Austin bahwa Filsafat Bahasa melingkupi fungsi bahasa, bertalian dengan tindakan manusia.
Teori Austin dipaparkan secara khusus pada bagian kedua dari buku ini. Oleh karenanya sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, inti dari buku ini dijelaskan pada bagian kedua. Penulis menjelaskan, sejak tahun 1940-an Austin telah memperkenalkan teorinya yang membagi ungkapan pada ungkapan performatif, ungkapan konstatif, dan tindak tutur. Namun perlu ditegaskan bahwa Austin tidak menulis buku. Teori-teori Austin di ambil dari makalah-makalah serta ceramah-ceramahnya di kampus pada saat itu. Di dalam perkuliahannya Austin memang kerap melontarkan ungkapan ‘what to say when’, yang dimaknainya bahwa unsur bahasa (what) sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena (when). Ungkapan ini oleh Austin dinamainya Linguistic Phenomenology.
Teori Linguistic Phenomenology yang diungkapkan oleh Austin menunjukkan bahwa ungkapan hanya sekedar nama untuk menyebut aktivitas analisis bahasanya, karena Austin tidak tertarik dengan analisis bahasa yang melihat bermakna-tidaknya suatu ungkapan bahasa hanya berdasarkan formulasi teori linguistik struktural. Bagi Austin, suatu ungkapan bahasa, selain berbeda ucapannya dengan ungkapan bahasa lain, juga berbeda dalam hal situasi penggunaan dan dampaknya bagi mereka yang terlibat di dalamnya.
Hal yang patut diperhatikan dalam bagian kedua buku ini, pada sub-tema ‘Aspek Penyembuh Bahasa’, penulis menjelaskan bagaimana keterhubungan antara Wittgenstein dan Austin. Keterhubungan ini terjadi disaat Austin menulis buku tentang Philosophical Investigation. Buku ini bertujuan dalam melakukan koreksi terhadap bukunya sebelumnya, yakni Tractatus Logico-Philosophicus, karena buku ini terasa sempit dalam memahami hakikat realitas, oleh karena hanya terbatas pada logika bahasa. Keterhubungan Austin dengan Wittgenstein dapat terlihat pada pemikiran Wittgenstein tentang fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari manusia, sebagaimana digambarkannya dalam Philosophical Investigation.
Wittgenstein dalam tata permainan bahasa, menyinggung tugas filsafat yang dikatakannya harus menyelidiki permainan-permainan bahasa yang berbeda-beda, menunjukkan aturan-aturan berlaku di dalamnya, dan menetapkan logikanya. Analisis bahasa tidak lagi harus didasarkan pada logika formal atau logika matematis, tetapi harus didasarkan pada dan diperlakukan dengan menggunakan bahasa biasa, the ordinary language, yakni bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Pemikiran Wittgenstein mengenai Filsafat Bahasa Biasa dikembangkan oleh para filsuf dari lingkungan Universitas Oxford seusai perang dunia II, terutama Austin. Pemikiran Austin tampak lebih khas dibandiingkan dengan pemikiran Wittgenstein, terutama pemikiran analitisnya tentang ungkapan performatif, ungkapan konstatif, dan tindak tutur.
Dalam sub-tema ‘Pemikiran Analitis Austin’ pada bagian kedua buku ini, penulis memaparkan posisi Austin sebagai seorang filsuf Filsafat Biasa dan memaparkan prinsip-prinsip utama pemikiran Austin. Austin berkeyakinan bahwa dari bahasa biasa sehari-hari akan banyak hal yang dapat dipelajari, mengingat banyaknya distinsi dan nuansa halus yang dikembangkan oleh para pemakai bahasa dari generasi ke generasi dalam rangka mengungkap segala realitas. Austin juga meyakini, tidak sedikit masalah filosofis yang akan tampak menjadi bentuk baru jika didekati dengan alat-alat yang terkandung di dalam bahasa sehari-hari.
Austin berprinsip bahwa penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari situasi konkret dan dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penggunaan bahasa tersebut. Prinsip ini oleh Austin dalam istilah lingusitik fenomenologis, yakni bagaimana menjelaskan fenomena melalui analisis bahasa. dari prinsipnya ini, Austin hendak menggarisbawahi bahwa linguistik hasruslah dilumuri dengan aspek fenomenologis, karena persoalan-persoalan di dalam Filsafat Bahasa Biasa merujuk pada dua hal utama: hal tentang ‘penggunaan yang biasa dari ungkapan’ (the ordinary use of the expression) dan hal tentang ‘penggunaan bahasa yang biasa’ (the use of ordinary language).
Menurut penulis, pada awalnya Austin membagi jenis-jenis ungkapan atas ungkapan konstatif (pernyataan) sebagai lawan dari ungkapan performatif (dekralatif). Ungkapan konstatif adalah jenis unngkapan bahasa yang melukiskan suatu keadaan faktual atau peristiwa nyata, yang oleh karena itu memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar-salahnya berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Kemudian ungkapan performatif adalah ungkapan yang berimplikasi dengan layak-tidaknya atau berbahagia-tidaknya (happy or unhappy) si penutur ketika mengungkapkannya. Itu sebabnya, ungkapan performatif sukar diketahui salah-benarnya, mengingat pertalian eratnya dengan kewenangan dan kelayakan si penuturnya. Oleh karenanya, Austin memberikan syarat atau ciri-ciri yang harus diperhatikan berkenaan dengan ungkapan performatif. Namun tidak sampai disini, persyaratan untuk ungkapan performatif ternyata juga berlaku bagi ungkapan konstatif.
Perbedaan hakiki diantara kedua bentuk ungkapan itu ternyata diragukan oleh Austin, terutama karena keduanya sama-sama terikat secara kontekstual pada seluruh situasi yang total kapan ujaran itu diungkapkan. Untuk mengatasi keragu-raguannya, Austin mengemukakan teori tindak tutur (speech acts), yaitu tindakan bahasa yang berperan ketika seseorang mengucapkan suatu kalimat. Teori tindak tutur yang dilandasi oleh pemikiran Wittgenstein itu, dibangun oleh Austin melalui tesis ‘dalam mengatakan sesuatu, berarti kita melakukan sesuatu pula’. Pada prinsipnya, tindak tutur menggarisbawahi bahwa perkataan dan tindakan adalah sama.
Selanjutnya Austin membagi membagi tindah tutur ke dalam tiga jenis, yakni (1) tindak lokusi (locutionary acts), (2) tindak ilokusi (illocutionary acts), dan (3) tindak perlokusi (perlocutionary acts). Tindak lokusi, yaitu tindak tutur penutur dalam menyampaikan sesuatu yang pasti, sekalipun tidak ada keharusan bagi si penutur itu untuk melaksanakan isi tuturannya. Tindak ilokusi, yakni tindak tutur penutur yang hendak menyatakan sesuatu dengan menggunakan sesuatu dengan daya khas, yang membuat si penutur itu bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Tindak perlokusi, yakni efek tindak tutur si penutur bagi mitra tuturnya. Dalam penegasan lain, bila tindak lokusi dan tindak ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, pada tindak perlokusi yang ditekankan adalah bagaimana respons mitra bicara.
Bagian ketiga dan keempat buku ini, memaparkan aspek aplikatif atau aksiologis teori Filsafat Bahasa Biasa. Sejak awal penulis menekankan pentingnya aspek aksiologis teori ini. Misalnya pada bagian pertama, penulis menkritisi mereka yang berunjuk rasa dengan membawa kerbau. Bagi Dr. Wibowo, si pembawa kerbau itu ternyata tidak memiliki keseimbangan antara akalnya dan bahasanya. Ia tidak mampu memahami bahwa kerbau bukan sekedar hewan yang berkolerasi dengan makna konotatif ‘gemuk’, ‘malas’, atau ‘bodoh’. Lebih dari hal itu, kata ‘kerbau’ itu sendiri mengandung unsur aksiologis sehubungan dengan nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat kita.
Contoh lainnya disaat menjelaskan ungkapan konstatif dan ungkapan performatif. Misalnya berkenaan dengan ungkapan konstatif, penulis memberikan contoh; “Saya ditugasi Presiden mengatasi luapan lumpur lapindo di Sidoarjo,” ujar mentri Pekerjaan Umum. Si saya atau Mentri Pekerjaan Umum di dalam berita itu sekedar diinformasikan oleh wartawan bahwa ia diberi tugas mengatsi luapan lumpur lapindo. Hal ini berarti benar-salahnya ungkapan ini tergantung faktanya apakah Pak Mentri benar-benar ditugasi oleh Presiden (melalui surat alat bukti tertentu, misalnya surat tugas).
Sementara contoh ungkapan performatif; “Luapan lumpur di Sidoarjo akan teratasi paling lambat akhir 2008,” ujar Mentri Pekerjaan Umum lebih lanjut. Si saya atau Mentri Pekerjaan Umum dalam berita itu sekaligus berjanji melakukan tindakan. Akan tetapi, ungkapan ini belum dapat ditentukan layak-tidaknya, sebelum janji si saya itu direalisasikannya. Dan banyak contoh-contoh lainnya dalam mengaplikasikan teori Filsafat Bahasa Biasa, khususnya pada bagian akhir atau bagian keempat buku ini.
Dalam meresensi buku ini, beberapa hal penting sebagai saran dalam membaca buku ini:
Salah satu kekuatan Buku ini, oleh karena penulis menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Khususnya dalam memberikan contoh-contoh aplikatif dari setiap teori-teori Filsafat Bahasa Biasa dalam buku ini. Hal tersebut sekaligus menunjukkan dalam mengaplikasikan Filsafat Bahasa Biasa. Dan juga membuktikan penguasaannya terhadap Filsafat Bahasa Biasa.
Buku ini adalah buku pengantar untuk memahami Filsafat Bahasa Biasa, khususnya dalam memahami pemikiran Austin. Oleh karenanya, disarankan pada pembaca yang ingin memahami lebih jauh, hendaknya membaca buku lainnya yang mengeksplorasi lebih jauh Filsafat Bahasa Biasa, khususnya pemikiran Austin. Sehingga terpahami dengan baik, bagaimana dan dimanakah sejarah lahir Filsafat Bahasa Biasa ini dimulai. Sekaligus memahami lebih jauh teori Speech Acts yang jejaknya diawali oleh Wittgenstein, kemudian Austin, lalu dikembang lebih jauh oleh muridnya, John Searle dalam karyanya “Austin on Locutionary and Illocutionary Acts”.
Hal lain yang belum tersentuh dalam buku ini juga menjadi catatan penting bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin meneliti lebih jauh terkait dengan pembahasan ini. Misalnya bagaimana peran Filsafat Bahasa Biasa terkaiat dengan bahasan agama. Sejauh manakah Filsafat Bahasa Biasa ini dapat diaplikasikan ke dalam ranah agama ?